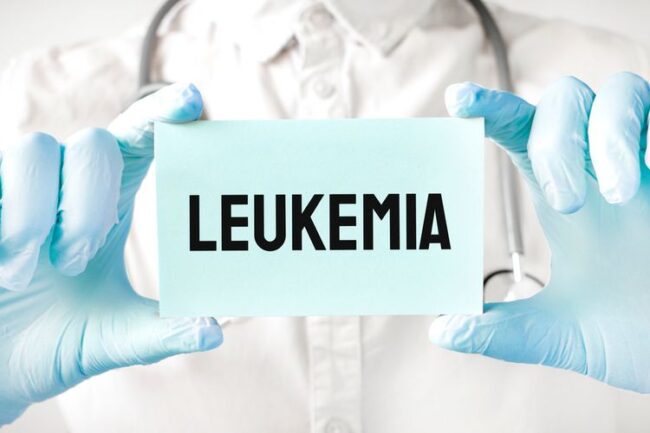REMAJA “molek” berhati “malaikat,” yang tutur halusnya meliuk bak gerai rambut ikalnya, ketika hari kami menjenguk di Minggu gerimis, pekan pertama Januari lalu, sedang beranjak meninggalkan jejak penyakit “langka”nya di ranjang sebuah kamar rawat inap Rumah Sakit Zainoel Abidin.
Hari itu, gadis berwajah bening itu, baru saja melewati ritual pengobatan “kemoterapi,” untuk kesekian puluh kalinya, sejak ia di vonis menderita leukemia jenis “a.l.l.” (leukemia linfositik akut). Penyakit “darah” yang kebanyakan diderita anak-anak dengan tendensi produksi darah putih yang mengalir dari sumsum tulang belakangnya berbiak “membunuh” darah merahnya.
Penyakit yang disepakati di dunia ilmu kedokteran sebagai “neoplasma,” kanker darah telah mengantarkan remaja belia itu melewati terapi farmasi kemoterapi, sebagai satu dari dua pilihan pengobatan, lainnya cangkok sumsum, yang memerlukan “persahabatan” antara semangat pasien, obat dan dokter untuk menuju satu kata, sembuh. Jalan penyembuhan itu pula yang menyebabkan luruhnya “mahkota” ikalnya, dan hari itu kepalanya dibalut kain selendang. Kepada kami ia mencandai dirinya dengan gurauan yang sangat khas remaja, ceplas ceplos, “Si Gadis Pelontos.”
Gadis “rembulan” berbadan semampai dan berkulit terang itu, hari kami bertakziah, antusias menyambung setiap ujung cerita ibunya yang berkisah runut tentang hari-hari terakhir upaya penyembuhannya. “Sudah mendingan Ndong,” katanya, menyapa kami di suapan terakhir nasi bungkus berkuah lemak, yang katanya amat mengasyikkan, usai dokter Heru, satu-satunya spesialis hemotologi di rumah sakit itu, berlalu mengecek kondisinya kesehatannya.
Cut Rika, nama gadis kecil peranakan Jawa, Minang dan Aceh itu, seperti dikatakan ibunya, Sri Rejeki, masih kuat menggenggam sisa harapan untuk sembuh setelah dua tahun terakhir mengembara bersama keluarganya mencari sumber penyakit, yang awalnya nyaris disimpulkan sebagai “kemasukan,” dari Tapaktuan hingga ke Medan, Penang dan balik ke Banda Aceh, yang menyebabkan kulitnya melepuh dan badannya menipis dengan rasa sakit, yang ia katakan dengan lugu,”tak tahu bagaimana harus dikatakan.”
Telah empat bulan Rika menghuni kamar kecil di Ruang Seruni yang asri di sudut rumah sakit “moderen” bantuan Jerman itu. Kondisinya, seperti dituturkan ayahnya, Oyong, masih “bergelombang.’ Tapi sudah menjauh dari “roller coaster.” “Naik turunnya tidak setajam dulu lagi. Ya, sudah mendingan,”ujar sang ayah.
Dulunya, ketika diagnosanya masih bergerak dari “kemunginan… ke ..kemungkinan,” “gelombang” tensi, trombosit dan “hb”nya sulit diprediksi. Kadang baik, yang membuat tampilannya bak remaja seutuhnya. Ceplas ceplos, dengan segumpal impian. Dan kala teman sekolahnya datang berhamburan senda ejek ber-hhaaa…hhii…hhuu.. tentang pe-er yang belum rampung.
“Dalam kesempatan yang sama ia bisa menjerit dan ambruk ketitik terendah sembari mendesahkan keinginannya untuk menghampiri kematian sebagai “obat”untuk mengakhiri rasa sakitnya. Pernah “hb”nya drop hingga ke angka dua. Subhanallah,” kata Oyong mengenang perjalanan penyakit anaknya dengan kepala menggeleng dan di pelupuk matanya muncul genangan air yang kemudian mengalir membentuk dua sungai kecil dipipinya.
Rika, tidak hanya sebuah kisah tentang penderitaan sebuah keluarga dalam menghadapi penyakit langka bernama kanker yang harga pengobatannya mahal, mewah, dan menguras emosi. Rika juga sebuah realitas keberuntungan karena hadir di sebuah dekade yang tepat ketika harga “mahal” pengobatan di negeri ini digilas program yang bernama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sebuah program, yang seperti dikatakan Oyong, bak “malaikat” yang menjulurkan dirinya ke takdir kami. Takdir ketika keputusan Oyong “mencampak”kan usaha toko bangunannya dan berkutat mencari harapan kesembuhan puterinya.
Kini, dengan keluarga kecilnya, Oyong punya dua anak lainnya selain Rika, telah memutuskan “hijrah” ke Banda Aceh untuk menjadi “nomaden” dengan menempati kamar gratis tempat anaknya di rawat di rumah sakit provinsi itu. “Saya sekarang penganggur. Makan dari pade bijeh,” katanya bercanda.
“Saya tidak pernah menghitung berapa rupiah yang sudah kami habiskan untuk mencari penyembuhan ini. Kami sepakat untuk menggenggam dengan kuat harapan kehidupan puteri kami. Dan setiap kali lorong hitam kematian menghampiri buah hati kami, kami berdoa ambilah semuanya kecuali dia” kata Oyong yang mengaku tak peduli dengan “kebangkrutan” usaha yang bengkalaikan di kampunya.
Harapan! Itulah yang tersisa ketika derita kami mengecil. Dan harapan itu pula modal kami ketika kesempatan penyembuhan itu datang bersama terbukanya pintu JKA sebagai basis biayanya, ” kata Oyong yang diiyakan anggukan derai air mata bahagia istrinya.
Dari harapan itu pulalah yang mempertemukannya dengan diagnosis final penyakit Rika, usai ia pulang dari Penang untuk kesekian kalinya. Leukemia. “Leukos” dan “aima.” Darah putih. Atau pupulernya kanker darah pada darah dan sumsum tulang belakang.
Harapan yang mempertemukannya dengan Dr Heru, spesialis “only one” hematologi di Rumah Sakit Zainoel Abidin. Pertemuan, yang ia katakan sangat membahagiakan. Pertemuan ketika Dr Heru mengatakan, tak ada masalah dengan pengobatan, perawatan dan biaya “penyembuhan” Cut Rika.
Penyembuhan berbasis pembiayaan JKA yang tak membatasi jenis penyakit, langka atau tidak langka, semacam leukemia yang menghabiskan dana ratusan juta.
Dan paling menyenangkan lagi ketika Dr Heru, anak muda yang baru saja menyelesaikan spesialis penyakit kelainan darah, yang gairahnya sedang membuncah mencari tahu ke hampir semua jurnal dan seminar kesehatan bagaimana upaya penyembuhan leukemia, eee….Rika. Pertemuan, seperti dikatakan Oyong, telah mempertautkan emosi keluarganya tidak hanya sekadar hubungan formal pasien dan dokter tetapi juga berbalut bersama label persaudaraan yang sangat “familiar” atas nama kemanusiaan.
Seperti diceritakan Oyong dalam sepenggal kasus, ketika Heru sedang mengikuti seminar di Kuala Lumpur dan jadwal “kemo” anaknya dititipkan kepada dokter jaga dan perawat khusus, Rika mengeluh kesakitan ketika “kemo” baru dimulai dan dia “ngambek.” Dan ketika Heru di “bbm” ia membalas, “sih oke, tunggu saja saya kembali.”
JKA, terlepas dari kelahirannya yang “compang-camping,” beraroma populis, tanpa konsep yang matang, ditambah lagi munculnya bayangan korupsi yang dihujat oleh banyak ngo anti korupsi sebagai “sarang” baru permainan uang publik, sempat disepelekan sebagai program “cet langet,” kini menjelma menjadi “malaikat” peretas “setan” yang bernama biaya.
Juga diawal ia digagas dan berjalan di tahun pertama muncul “badai” tuduhan tentang adanya “permainan” anggaran yang menuai tuntutan untuk mengauditnya. “Untung saja program itu tidak benar-benar menuai badai korupsi,” kata seorang penggagas awal yang enggan disebut namanya dengan kalem.
Bahkan, ketika “kampanye” Pilkada Gubernur tahun lalu, “mata” dagangan program ini “dijual” habis-habisan oleh Irwandi Yusuf, gubernur petahana waktu itu, dan membuat meriang setiap calon lainnya. Program yang mendongkrak angka hasil survei awal Irwandi ini menjadi biang permusuhan antar elitis tim sukses dan diayak dengan mengerucutkan persoalan dakwa dakwi proses pilkada ke ranah lain. “Sebenarnya calon lain takut dengan program ini dan membantai sang petahana lewat jalur politisasi isu lain. Ya sudah,” kata seorang pengamat.
Padahal diawal mencalonkan diri sebagai gubernur untuk kedua kalinya, Irwandi “memaksa” tim anggaran provinsi untuk menggelontorkan Rp 419 milyar untuk membiayai JKA, yang bararti mengalami kenaikan hampir dua kali lipat ketika saat pertama di canangkan 2010 dengan modal awal Rp 240 milyar. Dan tahun kedua 2011 besaran dana JKA Rp 261 milyar. Dana ratusan milyar ini dikelola oleh Askes lewat sebuah kesepakatan dengan Pemprov pada tanggal 1 Juni 2010 dan secara pertanggungjawabannya memenuhi syarat akuntabel.
Kesepakatan dengan sistem “universal coverage healt,” yang berati mengasuransikan semua penduduk Aceh yang memiliki identitas “katepe” dan tercantum dalam kartu keluarga tanpa melihat status sosial, agama dan asal usulnya. Semua mereka bisa mengakses fasilitas pengobatan dan perawatan di instalasi kesehatan yang ada di Aceh.
Setelah menjelma menjadi realitas kebijakan yang sangat merakyat, bahkan “spektakuler,” JKA tidak hanya menyentuh Oyong, tapi juga memboyong warga yang sakit menahun di perkampungan marjinal dan berbondong-bondong menghuni sal-sal rumah sakit. Program, yang seperti dikatakan seorang kawan, yang di awalnya mengritik dengan tajam pelaksanaannya, telah menyelamatkan semua penduduk yang ber”katepe” Aceh dari “kemewahan” pengobatan yang durasinya dilabel dengan kata “gratis.”
Oyong mengisahkan bagaimana obat leukemia dan kemoterapi yang memerlukan order khusus dengan harga belasan juta rupiah sekali tebus bisa sampai ke ruang inap anaknya tanpa ia mengeluarkan uang satu rupiah pun. Oyong juga tak mengalami kesulitan menebus obat ke apotik atau berurusan dengan pelunasan tagihan sewa kamar yang dihuni puterinya berbulan-bulan.
Lelaki paruh baya itu, seperti juga keluarga pasien yang lainnya, cukup menandatangani formulir pertanggungjawaban bersama dokter dan petugas administrasi rumah sakit. “Sederhana,” ucap Oyong yang pernah menghitung sendiri total biaya pengobatan puterinya. “Wooow.. ratusan juta rupiah,” katanya mengernyitkan dahi. Dengan bergurau ia mengatakan, “kalau banyak pasien penderita leukemia bisa bangkrut JKA.”